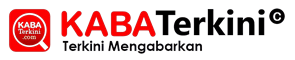“Aku ikut.”
Sebelum Astra memecah ketegangan itu. Kembali ke malam pertempuran, Dirga kini berdiri dengan senjatanya terselip di pinggang. Ia tak lagi mengantuk, melainkan dipenuhi kefokusan yang hampir terasa dingin.
Tujuh orang ini, termasuk dirinya sendiri, adalah inti dari pasukan ini. Tetapi di luar sana, puluhan pengikut setia menanti sinyal mereka. Dan tentu, mereka tahu pasti resiko malam ini: tak lebih dari sekadar pemberontak yang akan digantung jika semisalnya mereka gagal.
“…Ingat kode kita!” Perintah Dirgantara.
Ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh ke belakang, melihat Rodra, seorang pria yang terkenal sangat tenang, anak dari dokter Kasunanan yang telah Dirga kenali sejak kecil.
“Dirga, izinkan aku pergi bersamamu.” Ujarnya,
“Aku akan menjaga punggungmu.” Dirga tersenyum.
“Tentu. Ayo buat VOC menyesal telah datang ke tanah ini.” “Terima kasih, ini suatu kehormatan.” Rodra mengangguk.
Mereka memulai serangan pada saat lawan mereka sedang tidur cantik di kasur mereka, atau halusnya: serangan mendadak.
Hebatnya, rencana mereka hampir sempurna, Belanda tidak siap dan mereka berhasil melumpuhkan pos penjagaan utama. Suara tembakan dan teriakan bercampur dengan kegembiraan yang membuncah. Mereka tak menginginkan perang, mereka hanya perlu gangguan masif agar Kasunanan dapat mengambil kembali kendali. Dan mereka hampir berhasil.
Tinggal sedikit lagi. Di ujung terowongan yang gelap itu, ia bisa melihatnya. Cahaya yang Dirgantara janjikan. Cahaya yang mereka semua impikan. Dirga berada di depan, memimpin penyerbuan ke ruang penyimpanan peta, tempat dokumen-dokumen penting VOC.
Ketika ia berbalik, hendak meneriakkan perintah pada Astra dan yang lain. Saat itulah ia melihatnya. Rodra berdiri di sana, persis di belakangnya. Wajah tenang, dingin dan kosong.
Ia memegang pistol kecil dengan ukiran perak, jelas bukan senapan Jawa. Semua kemungkinan berlari melalui pikiran Dirgantara saat dia mulai memahami segala maksud dari situasi ini. Matanya melebar, dan Rodra pun menyeringai samar dengan sadisnya, menodongkan pistol Eropa itu.
“Rodra… Bagai-” Suaranya serak, di atas bisikan. “Teganya kau…” “Maaf, Dirgantara.” Rodra terkekeh, seolah dia mendapatkan kesenangan yang menyimpang melihat kesakitan rasa terkhianati di matanya.
“Mereka menawarkan hal-hal yang tak bisa kau berikan: Kuasa sejati, bukan hanya janji.”
Sebelum Dirgantara sempat bersuara lagi, sebelum ia sempat meregistrasi pengkhianatan ini, sebelum ia sempat memikirkan nasib yang lain jika ia tumbang, ada kilatan api yang sangat singkat tepat di dadanya.
Telinganya berdengung selagi ia terjatuh ke lututnya. Rasa sakit di dadanya jauh lebih dari sekedar kondisi fisik. Hatinya serasa hancur, nafasnya pun menjadi berat. Dengan keras kepala dan tenaga kehidupan yang tersisa padanya saat itu, Dirgantara mendongak dan menantang mata Rodra. Dan dengan bersusah payah, ia menyatakan dengan lantang:
“Hindia-Belanda akan bebas. Ingat itu.” Mata Rodra menyipit dengan kepahitan. “Sudah diamlah dan mati sana.”
Penghianat itu mengangkat pistolnya lagi, dan pandangan Dirga menjadi kosong. Dirgantara jatuh ketanah, semua perjuangan dan mimpinya telah berakhir.
Semua terasa begitu dekat namun begitu jauh. Revolusi 1791 di Surakarta gagal sebelum sempat tercatat dalam sejarah, hanya dikenang sebagai bisikan tragis seorang pemimpin.
Di saat terakhirnya, Dirga meyakini kebebasan Hindia-Belanda, bahkan jika dunia itu ada jauh dari sini. Ia harus melewatkannya, karena dunia itu jauh melampaui usianya.***