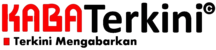Mudik, Rakik-rakik, dan Lamang di Sumatera Barat
Oleh: Muhammad Arif Efendi
KABATERKINI.Com – Penggalan syair lagu dari Band Gigi berjudul ‘Selamat Hari Lebaran’ menjadi penggugah bagi penulis untuk sedikit mengulas tradisi ‘mudik’ yang setiap tahun dilakukan masyarakat Indonesia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘mudik’ berasal dari kata ‘udik’ yang mengandung makna dusun, desa atau kampung. Biasanya ‘udik’ terkesan cenderung berkonotasi negatif, bahkan sampai dikaitkan dengan kebodohan, kejumudan, ketertinggalan atau kampungan.
Padahal, dalam pengertian lebih luas, mudik bermakna mereguk kembali semangat kampung yang identik dengan gotong royong, kesetiakawanan, kebersahajaan, dan persaudaraan untuk dibawa lagi bila para pemudik kembali ke komunitas di mana mereka tinggal. Ada pula yang menyebut bahwa ‘mudik’ berasal dari bahasa Jawa Ngoko, yakni ‘mulih dilik’ yang berarti ‘pulang sebentar’.

Menurut Antropolog Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Heddy Shri Ahimsa Putra, ‘mudik’ berasal dari bahasa melayu ‘udik’ yang artinya hulu atau ujung. Sebab, masyarakat Melayu yang tinggal di hulu sungai pada masa lampau sering bepergian ke hilir sungai menggunakan perahu atau biduk. Setelah selesai urusannya, mereka kembali pulang ke hulu pada sore harinya. Saat orang mulai merantau ke kota-kota besar, kata ‘mudik’ mulai dikenal dan dipertahankan hingga sekarang saat mereka kembali ke kampung halaman atau tempat kelahiran.
Sementara, pada laman situs Kementerian Perhubungan RI dijelaskan bahwa istilah ‘mudik’ mulai muncul pada 1970-an. Saat itu, Jakarta masih merupakan satu-satunya kota besar di Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah mengadu nasib ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Ada yang bekerja di kantor-kantor pemerintah, swasta, pabrik, industri, bahkan ada juga yang menjadi pengusaha.
Bagi para perantau, kembali ke kampung halaman terlebih, saat lebaran, menjadi moment tersendiri dan mempunyai makna yang lebih, dan hal ini disebut dengan ‘mudik’. Mudik menjadi momentum terbaik bagi para perantau untuk melepas rindu dengan keluarga, sanak saudara di kampung halaman. Bahkan fenomena ‘mudik’ ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja, tetapi sudah menjadi tradisi tahunan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia.
Umumnya, orang memilih mudik sebelum Syawwal, tak menutup kemungkinan beberapa yang lain, memilih setelahnya. Pada dasarnya, mudik merupakan istilah umum yang disematkan pada mereka yang pulang kampung dan tidak terbatas pada periode waktu tertentu.
Setiap orang yang pulang kampung disebut mudik. Namun pada perkembangannya, mudik diartikan sebagai pulang kampung saat menjelang lebaran. Alasannya, lebaran merupakan momentum yang paling banyak dimanfaatkan untuk pulang kampung karena sering dikaitkan dengan perjalanan spiritual yang sarat makna, selain pemerintah juga biasanya menetapkan waktu libur nasional cukup lama.
Hingga pada akhirnya, jika kata mudik itu disebut, secara spontan masyarakat Indonesia akan membayangkan mudik lebaran dengan segala hiruk pikuknya yang menyita waktu, mulai dari perjalanan yang panjang, macet, berdesak-desakkan, panas, dan lain sebagainya. Tetapi, semua itu tidak mengurangi semangat masyarakat Indonesia untuk tetap mudik ke kampung halaman.
Masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan terbentang luas di banyak pulau-pulau, tradisi mudik ini menjadi daya tarik tersendiri baik dari sisi budaya, sosial, serta agama dan spritual. Primordialisme (kedaerahan) menjadi identitas yang begitu mengakar dan kuat. Siapa pun yang merantau pasti rindu pulang ke kampung dan berkumpul bersama sanak keluarga dan handai tolan. Seberapa pun jauhnya merantau, pada akhirnya seseorang akan kembali ke asalnya.
Pepatah mengatakan, “setinggi-tinggi bangau terbang, ia akan kembali ke sangkarnya”.
Tradisi mudik telah menjadi ritual bagi umat muslim Indonesia, tidak peduli ia berasal dari golongan kaya atau miskin, pekerja kantoran mau pun buruh pabrikan, atau bahkan pengepul asongan.
Berbagai alasan turut menyertai para pemudik, seperti rindu kampung halaman, sungkem kepada orangtua, silaturahmi dengan sanak saudara, dan berbagi kebahagiaan, kebersamaan dengan sesama.
Mudik sebenarnya adalah bentuk kebutuhan psikologis atau kebatinan. Di mana timbulnya dorongan keinginan dan kerinduan yang kuat untuk pulang menapak tilas tempat lahir dan tempat yang menyimpan memori dan masa lalu sebagai anak-anak hingga dewasa. Ini merupakan kerinduan psikologis-primordial.
Di Indonesia, momentum lebaran dan mudik didukung oleh pembenaran ajaran agama untuk menyampaikan bakti dan permohonan maaf kepada keluarga, khususnya orangtua.
Dalam buku ‘Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi’ (2003:29), Komaruddin Hidayat menuliskan bahwa, manusia itu homo festivus. Sebagai homo festivus, manusia adalah makhluk yang paling sering mengadakan festival, pada praktiknya berbalut budaya perkembangan zaman. Sembari dalam kerangka ritus keagamaan berlangsung, adat kebiasaan menambah semarak sebuah festivus. Festival di sini mengemban tiga misi.
Pertama, mengenang budaya dan tradisi lama. Kedua, mengenalkan tradisi (lama) itu kepada generasi baru. Ketiga, memperhadapkan tradisi lama pada situasi hari esok berupa penguatan budaya. Nah, mudik itu juga merupakan acara festival. Ada upaya mengenang (tradisi) masa lalu, mengenalkan tradisi itu kepada anak-anak sekarang serta memprediksi peluang pengembangan nilai tradisi untuk hari esok.
Dalam dunia semiotik, Ferdinand de Saussure yang berperan besar dalam pencetusan teori Strukturalisme sekaligus yang memperkenalkan konsep semologi (sémiologie; Saussure, 1972: 33), mengulas pendapatnya tentang langue sebagai sistem tanda yang mengungkapkan gagasan, ada pula sistem tanda alphabet bagi tuna wicara, simbol-simbol dalam upacara ritual, dan tanda dalam bidang militer. Kaitannya dengan tradisi ‘mudik’ jika dibaca dari sudut pandang semiotik, akan timbul bermacam pemaknaan atau tanda dalam struktur kehidupan setiap daerah.

Seperti halnya di Sumatera Barat, misalnya, ketika ‘mudik’ saat lebaran selain sebagai ritus atau kultur anak rantau yang rindu suasana kampung halaman dan segala macam kebiasaannya, juga dapat menyaksikan tradisi yang tak dapat dilihat selain saat lebaran yakni festival rakik-rakik. Festival ini masih ada di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Festival ini digelar oleh lima jorong yang ada di Nagari Maninjau, yaitu Jorong Gasang, Jorong Pasar Maninjau, Jorong Kubu Baru, Jorong Bancah dan Jorong Kukuban.
Sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat di Nagari Maninjau sudah melaksanakan festival rakik-rakik sebagai tradisi dalam menyambut datangnya 1 Syawal. Acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama masyarakat. Sebab saat pelaksanaan festival rakik-rakik ini dimungkinkan dapat bertemu dengan sanak saudara dan teman lama.
Selain itu, biasanya rakik-rakik dibuat secara gotong royong oleh pemuda setempat. Dan pembuatannya dimulai sejak awal Ramadhan, sehingga pada malam takbiran rakik-rakik dilepas ke tengah Danau Maninjau.
Pada 1956, Roland Barthes yang membaca karya Saussure: Cours de linguistique générale melihat adanya kemungkinan menerapkan semiotik ke bidang-bidang lain. Barthes mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan Saussure mengenai kedudukan linguistik sebagai bagian dari semiotik. Menurutnya, sebaliknya, semiotik merupakan bagian dari linguistik karena tanda-tanda dalam bidang lain tersebut dapat dipandang sebagai bahasa, yang mengungkapkan gagasan (artinya, bermakna). Ini merupakan unsur yang terbentuk dari penanda-petanda, dan terdapat di dalam sebuah struktur.
Kelitkelindan dari pembacaan Roland Barthes ini sejalan dengan ‘mudik’ di saat lebaran dengan makanan khas ‘Lamang’. Mudik sebagai penanda bulan Ramadhan akan berakhir dan syawal akan tiba. Petanda-nya bulan Syawal tiba lebaran dan makan Lamang di kampung halaman.
Tradisi ma-lamang merupakan suatu budaya yang diwariskan secara turun temurun dan berkembang di lingkungan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman (sebagian besar Sumatera).
Bila diperhatikan secara sekilas, ma-lamang terkesan hanya merupakan proses atau cara memasak lamang (lemang) dengan menggunakan media bambu yang kemudian di bakar di atas bara api. Padahal, tradisi ma-lamang tidak hanya soal kemahiran memasak lemang, namun tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan sejarah yang membuat tradisi ini bertahan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Semarak tradisi ma-lamang, biasanya akan terasa pada peringatan hari-hari besar Islam, yakni menjelang bulan Ramadan, lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha), peringatan Maulid Nabi, baralek (pesta pernikahan), peringatan hari kematian, dan sebagainya.
Mayoritas masyarakat di Padang Pariaman menyakini, sejarah tradisi Ma-Lamang tidak dapat dilepaskan dari peran dan perjuangan Syekh Burhanuddin untuk menyiarkan agama Islam di Minangkabau. Ma-lamang dapat dikatakan metode dakwah yang digunakan oleh Syekh Burhanuddin untuk mengajarkan perbedaan makanan halal dan haram dalam ajaran Islam kepada masyarakat di daerah Ulakan, Padang Pariaman. (baca : Refisrul, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 3 : 2017).
Secara filosofis, tradisi ma-lamang juga menggambarkan nilai-nilai gotong royong dan semangat kebersamaan. Hal ini tergambar ketika saat ma-lamang hendak tiba, pada pagi hari, masyarakat yang terdiri dari laki-laki dewasa dan beberapa anak yang diajak membantu pergi mencari bambu dan kayu bakar untuk memasak lamang. Di rumah, para ibu-ibu dibantu oleh anak perempuan mereka di setiap rumah mulai memasak bahan-bahan untuk isian lamang. Setelah bambu dan kayu bakar sudah didapat, bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar pada sore hingga malam harinya. Wallahu’alam Bisshowab… *
(Penulis adalah Pranata Humas pada Biro Humas Data dan Informasi, Setjen Kemenag RI)